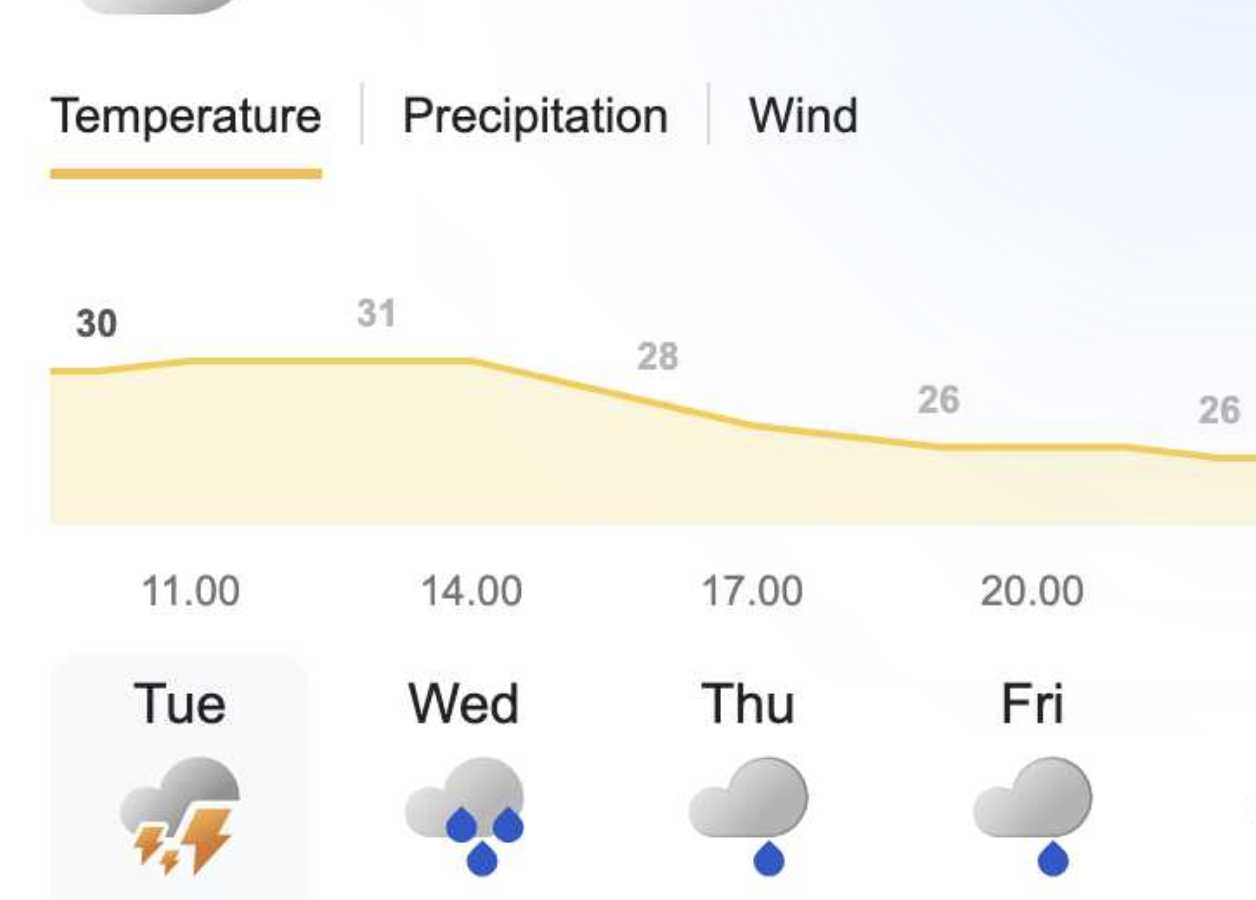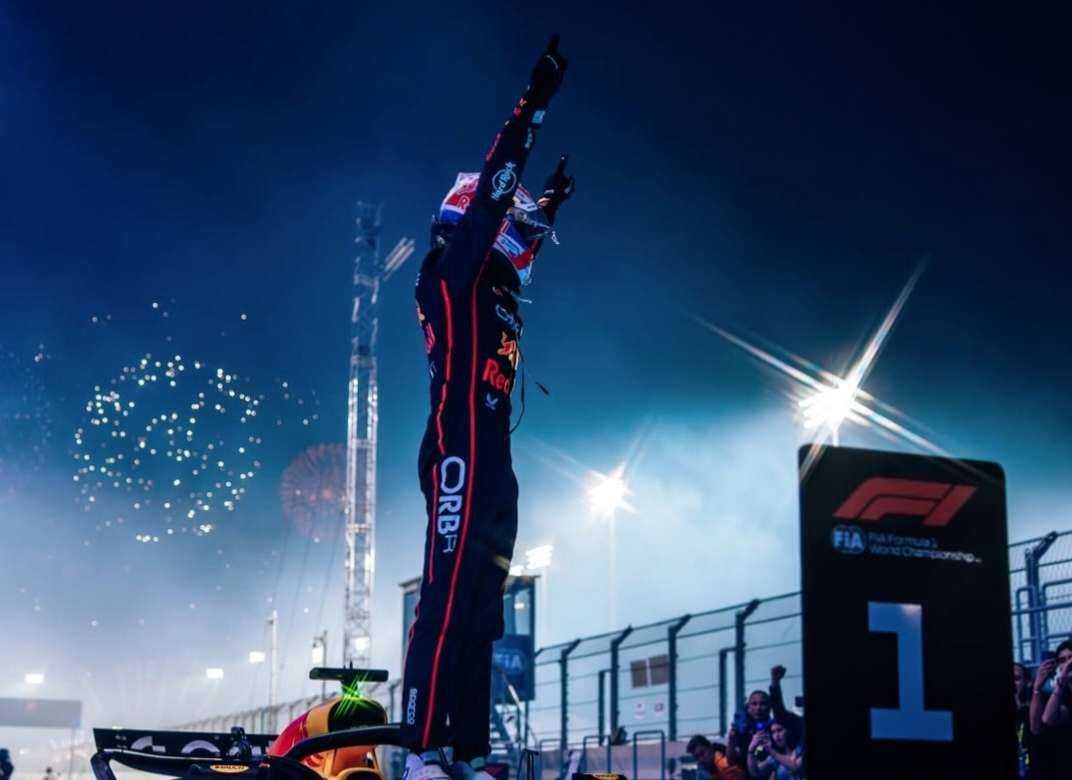Writer: fypmedia - Rabu, 09 Oktober 2024 08:00:00

FYPMedia.ID - Pada 7 Oktober 2024, dunia memperingati satu tahun sejak puncak serangan brutal yang banyak digambarkan sebagai genosida terhadap rakyat Palestina. Kekerasan ini tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga trauma mendalam, terutama pada anak-anak. Dalam situasi yang penuh ketakutan, kehilangan, dan ketidakpastian, anak-anak Palestina menjadi saksi langsung kekejaman perang, membawa luka emosional yang sulit sembuh. Bagi mereka, masa kecil yang seharusnya dipenuhi keceriaan kini tergantikan oleh bayang-bayang kekerasan yang mengerikan.
Trauma perang seringkali lebih sulit disembuhkan dibandingkan luka fisik. Pada anak-anak yang hidup di wilayah konflik, pengalaman menyaksikan kematian, kehancuran rumah, dan hilangnya orang yang dicintai menciptakan luka emosional dan trauma yang sulit diatasi. Setiap hari mereka dihadapkan pada ketakutan akan serangan mendadak, suara bom, dan ancaman konstan terhadap keselamatan mereka.
Dilansir dari Republika.id, seorang anggota staf Save the Children di Gaza dan ayah dari tiga anak di bawah usia 10 tahun, mengungkapkan betapa besar rasa kehilangan dan penderitaan yang mereka rasakan. "Kami hidup dalam ketakutan, tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa jam ke depan, atau esok hari. Kematian ada di sekitar kami. Setiap hari, anak-anak saya menatap mata saya, mencari jawaban. Tapi saya tidak punya jawaban untuk mereka," kata yousef.
Pada tahun 2023 Sekitar 80 persen anak-anak melaporkan perasaan takut, khawatir, dan sedih terus-menerus. Sementara, tiga perempat anak-anak mengompol karena ketakutan, dan semakin banyak anak yang menunjukkan gejala bisu reaktif hal ini menandakan trauma pada anak.
Dikutip dari Antaranews.com Dr. John Kahler, seorang dokter anak dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di zona krisis. Dia berkunjung Kembali setelah Pembangunan bangsal anak di Rumah Sakit Nasser di Kota Khan Younis, wilayah selatan Gaza pada 2019. Saat ia kembali pada Januari 2024, dia merasa kaget dengan pemandangan Gaza sekarang. Dia mengatakan bahwa kehancuran begitu parah sehingga ia hampir tidak bisa lagi mengenali tempat-tempat yang pernah dikunjunginya.
"Dulu ada jalan yang bagus di sepanjang pantai. Sekarang hancur total. Ketika kami sampai di rumah sakit, saya bertanya kepada pengemudi yang membawa saya, kapan kami akan melewati area universitas, dan dia berkata, 'Anda sudah melewatinya.' Universitas yang dulu ada di sana sudah rata dengan tanah. Semua empat universitas hancur total.â€
Di pusat kesehatan primer, ada ruangan khusus di mana Kahler dan timnya harus membersihkan luka pasien, terutama anak-anak, tanpa anestesi.
"Jadi, ada tangisan dan jeritan yang terdengar dari pukul delapan pagi hingga pukul lima sore, dan saya masih mendengar tangisan itu di malam hari. Saya terbangun mendengar anak-anak itu menangis, menjerit," katanya.
Banyak anak yang dirawat Kahler di Rafah menderita hepatitis A, penyakit menular yang dapat menyebabkan demam, muntah, dan, yang paling berbahaya, diare.
"Hampir 100 persen mengalami diare, yang merupakan penyebab utama kematian di kalangan anak-anak kecil," Ucap Kahler.
Sejak Israel memulai perang genosida di Gaza, sekitar 96 persen dari 2 juta penduduknya berada di ambang kelaparan, "Saya melihat orang tua tidak bisa memberi makan anak-anak mereka, meskipun mereka bisa, kerusakan akibat malnutrisi sudah terjadi." "Ini bukan hanya soal kekurangan kalori," katanya, menjelaskan bahwa perang telah menghancurkan masa depan seluruh generasi. Menurut Kahler, anak-anak yang kelaparan sejak lahir "akan membawa bekas luka trauma ini seumur hidup, baik secara fisik maupun mental." Tambahnya.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi warga Palestina dalam mengatasi trauma dan penyakit akibat perang adalah kurangnya akses ke layanan kesehatan. Blokade yang berkepanjangan dan serangan yang terus-menerus membuat sulitnya mendapatkan bantuan psikologis yang memadai. Meski banyak organisasi internasional mencoba memberikan dukungan, kebutuhan yang begitu besar membuat upaya ini belum mampu menjangkau semua yang membutuhkan.