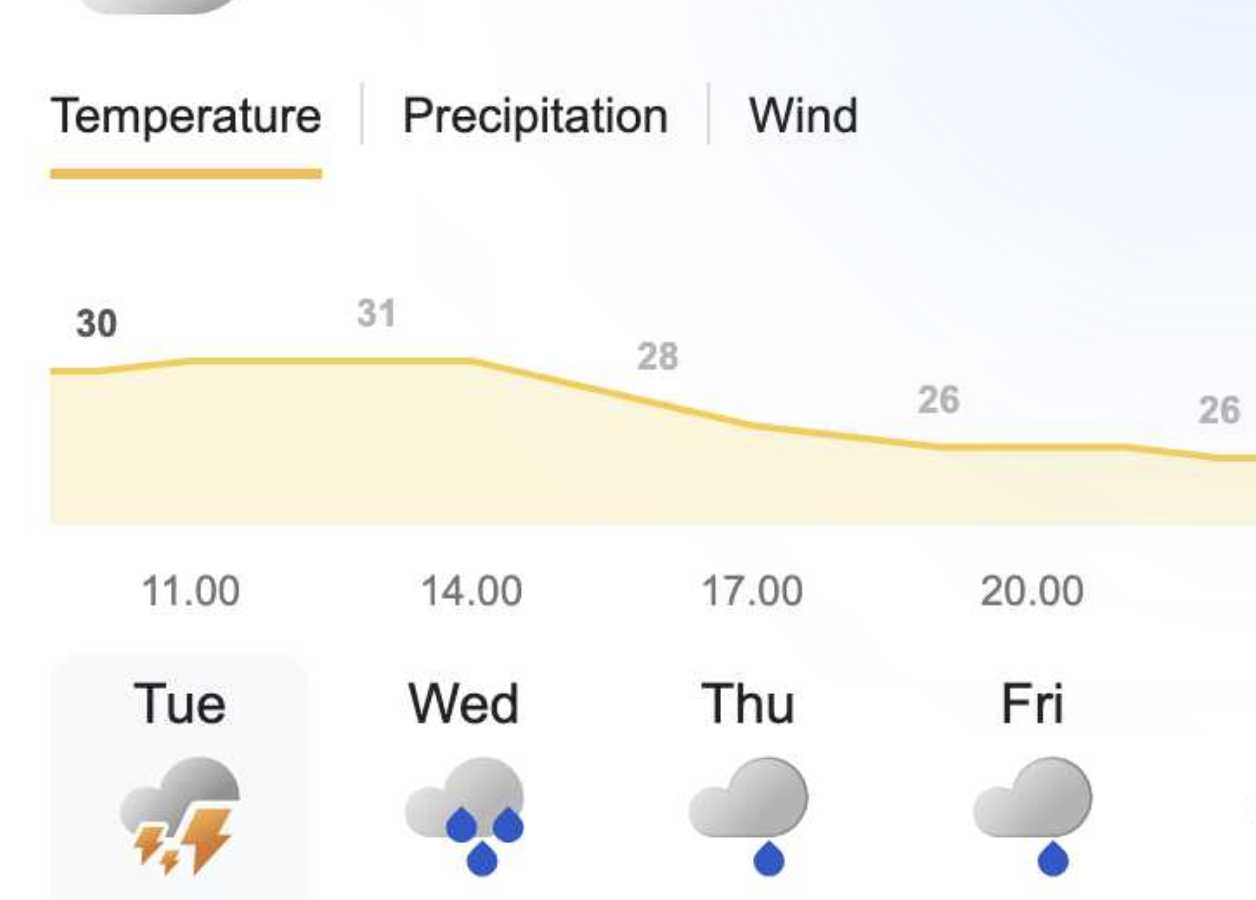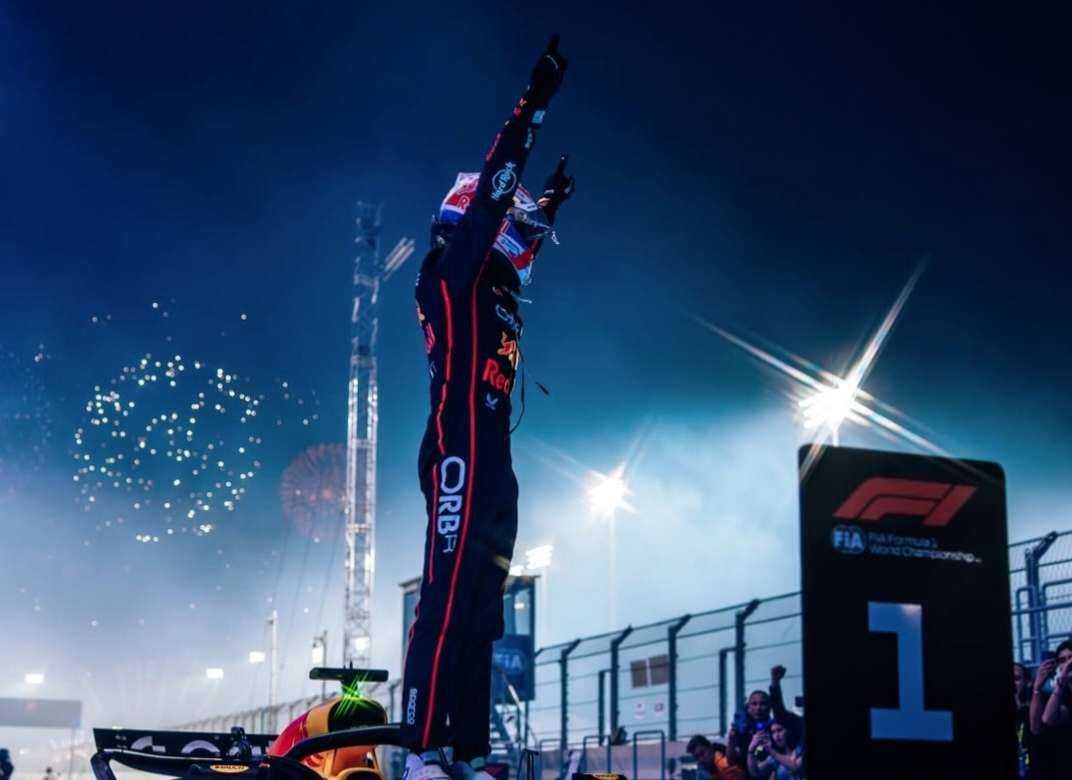Writer: Muhammad Riyadz Aqsha - Senin, 18 Agustus 2025 08:00:00

FYPmedia - Dunia kerja sedang mengalami gelombang baru fenomena pengunduran diri massal dari kalangan generasi Z, terutama di sektor digital dan startup. Alasan utama yang banyak dikemukakan adalah "burnout digitalâ€, yaitu kelelahan mental dan emosional akibat tekanan kerja online yang terus-menerus, multitasking ekstrem, dan ekspektasi produktivitas yang tidak realistis di era digital-first.
Apa Itu Burnout Digital?
Burnout digital adalah kondisi stres kronis yang timbul karena paparan teknologi tanpa henti, notifikasi kerja sepanjang waktu, pertemuan virtual yang padat, dan minimnya batas antara ruang kerja dan ruang pribadi. Gen Z, yang dikenal sebagai generasi paling melek digital, justru menjadi kelompok paling rentan karena sebagian besar karier awal mereka dibangun di lingkungan kerja hybrid atau full remote.
Banyak dari mereka mengaku kehilangan motivasi, merasa hampa, dan mengalami gangguan kesehatan mental karena tekanan terus-menerus dari pekerjaan digital yang seolah tak pernah selesai. Batasan antara waktu kerja dan waktu istirahat nyaris hilang, terutama ketika aplikasi kerja seperti Slack, Zoom, dan WhatsApp terus aktif di luar jam kantor.
Lonjakan Angka Resign Usia 20–30 Tahun
Laporan dari beberapa platform rekrutmen seperti JobStreet dan LinkedIn menunjukkan adanya peningkatan angka pengunduran diri usia 20–30 tahun sebesar 18% dalam setahun terakhir. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara dengan industri digital berkembang pesat seperti Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat.
Banyak perusahaan bahkan kewalahan menghadapi tingginya turnover karyawan muda yang meninggalkan pekerjaannya tanpa rencana jangka panjang. Beberapa dari mereka memilih untuk sabbatical, membangun bisnis kecil, menjadi freelancer, atau bahkan pindah ke sektor yang lebih "tenang†seperti agribisnis, pendidikan, atau seni kreatif.
Perspektif Psikologi dan Sosial
Psikolog industri menilai bahwa Gen Z memiliki tingkat kesadaran mental health yang jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Mereka tidak ragu mundur dari pekerjaan yang dianggap merusak kualitas hidup, meski berisiko secara finansial. Pola pikir ini dipengaruhi oleh lingkungan digital yang membuat mereka lebih cepat terpapar informasi soal self-care, healing, dan pentingnya work-life balance.
Selain itu, budaya hustle yang dulu diagungkan kini mulai ditinggalkan. Istilah seperti quiet quitting, career detox, dan mental health reset menjadi pembicaraan umum di komunitas Gen Z profesional.
Respon Perusahaan: Fleksibilitas atau Kehilangan Talenta?
Menghadapi tren ini, perusahaan mulai melakukan adaptasi. Beberapa strategi yang diterapkan adalah:
- Menerapkan 4-day work week
- Menyediakan cuti burnout
- Menawarkan akses ke psikolog atau life coach Memberikan opsi kerja hybrid yang lebih fleksibel
- Menciptakan budaya kerja yang suportif dan tidak toksik
Untuk mengatasi burnout digital, kolaborasi antara pekerja dan perusahaan sangat penting. Gen Z perlu diberi ruang untuk menyuarakan kebutuhan mereka tanpa takut dicap tidak loyal atau lemah mental. Di sisi lain, HR dan manajemen perlu memahami bahwa produktivitas jangka panjang hanya bisa dicapai bila kesehatan mental dan keseimbangan hidup pekerja dijaga.
Pendidikan sejak dini tentang manajemen stres digital, pengaturan waktu kerja, serta budaya kerja yang sehat bisa menjadi langkah awal agar fenomena ini tidak terus meluas. (ra)